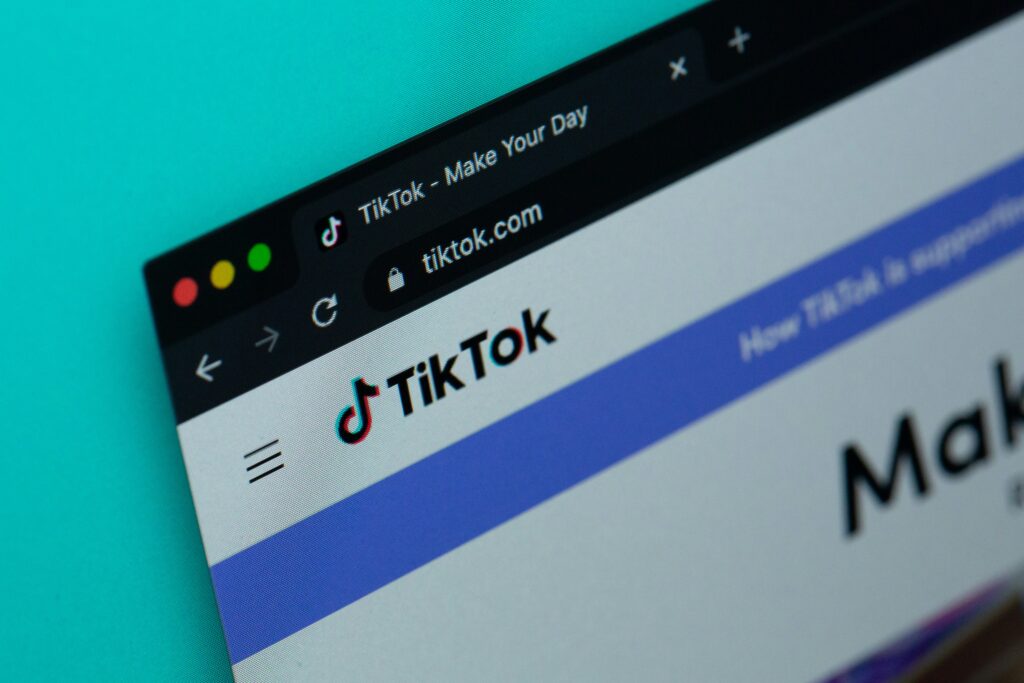Di TikTok, seorang kreator membuka bal pakaian bekas asal Korea. Ia menampilkan satu per satu jaket, kaus, dan celana yang konon “jarang ada di Indonesia.” Komentar berdatangan: “Wah, itu ori Jepang, Kak!” atau “Aku juga dapet Coach dari bundle kemarin.” Yang jarang ditanyakan adalah: darimana sebenarnya asal-usul baju-baju ini? Dan mengapa Indonesia tampak sangat ramah menampungnya?
Fenomena bisnis thrifting di Indonesia kian marak. Dari pasar-pasar tradisional hingga Instagram dan TikTok Shop, barang bekas kini tampil sebagai simbol gaya hidup baru: murah, unik, dan katanya ramah lingkungan. Namun di balik popularitasnya, tersimpan pertanyaan besar: apakah ini tren yang berkelanjutan, atau justru bentuk lain dari pelimpahan limbah global?
Thrift sebagai Tren dan Identitas Urban
Bagi anak muda urban, thrifting bukan hanya aktivitas belanja murah. Ia telah menjelma menjadi gaya hidup yang menyuarakan keunikan, kesadaran lingkungan, dan penolakan terhadap fast fashion. Tagar #thrifthaul atau #ootdthrift membanjiri media sosial, memperlihatkan betapa thrift menjadi bagian dari identitas digital.
Tidak sedikit pelaku usaha lokal yang mengandalkan thrift sebagai ladang bisnis. Dengan modal satu bal (bundle) pakaian bekas impor, mereka bisa menyortir, mencuci, memoles, lalu menjualnya kembali dengan nilai yang berkali-kali lipat. Narasinya pun kuat: ini bukan sekadar jual beli baju bekas, tapi bagian dari gerakan fashion sirkular.
Asal Barang: Dari Negara Maju ke Pasar Berkembang
Sebagian besar barang thrift yang beredar di Indonesia berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Eropa. Barang-barang ini dikumpulkan sebagai donasi atau limbah tekstil, kemudian diekspor dalam jumlah besar ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Masuknya barang bekas ini sering kali berada di wilayah abu-abu regulasi. Beberapa masuk secara legal dengan klasifikasi sebagai “barang bekas layak pakai” atau “tekstil daur ulang.” Namun tak sedikit pula yang masuk secara ilegal, disamarkan sebagai donasi atau tidak melalui jalur bea cukai resmi.

Celah Regulasi: Saat Definisi Jadi Kabur
Salah satu alasan mengapa arus masuk barang bekas ini sulit dikendalikan adalah tidak jelasnya definisi antara limbah, barang bekas, dan komoditas daur ulang di Indonesia. Dalam sebuah riset oleh Wijaya (2017), ditegaskan bahwa ketimpangan definisi waste antarnegara membuka ruang eksploitasi regulasi di negara berkembang. Apa yang dianggap limbah di Jepang bisa saja masuk sebagai barang dagangan di Indonesia.
Ketika negara-negara maju menerapkan regulasi ketat soal ekspor limbah (termasuk pakaian), Indonesia belum memiliki sistem klasifikasi dan pengawasan yang memadai. Ini menjadikan kita secara tidak langsung sebagai “terminal akhir” dari surplus fashion global.
Bisnis Cuan, Beban Lingkungan
Bagi pelaku thrift, margin keuntungan dari satu bal pakaian bekas bisa sangat besar. Namun, baju yang tidak laku, rusak, atau tidak memenuhi standar pasar akhirnya tetap menjadi sampah. Bedanya, kini sampah itu berada di pasar domestik—diangkut ke TPA, dibakar, atau dibuang sembarangan.
Thrift dalam bentuk ini bisa menjadi bentuk greenwashing struktural—di mana gaya hidup hijau diklaim, padahal limbah tetap bergulir. Konsumen membeli karena murah dan tren, bukan karena sadar akan daur ulang. Bahkan, banyak konten thrift haul justru mendorong belanja impulsif.
Perlu Tegas: Bukan Anti-Thrift, Tapi Pro-Kejelasan
Thrifting lokal bukan musuh. Justru, ketika didorong dari sumber domestik, thrift bisa menjadi kekuatan ekonomi sirkular yang inklusif dan berkelanjutan. Namun jika yang kita benarkan adalah arus masuk pakaian bekas impor yang tidak transparan asal-usulnya, maka kita hanya memperpanjang umur limbah dari utara ke selatan dunia.
Indonesia perlu menyusun ulang definisi hukum soal barang bekas, limbah, dan produk daur ulang. Regulasi impor harus memperjelas batasan. Pelaku usaha perlu lebih transparan soal asal barang, dan konsumen perlu lebih kritis terhadap apa yang mereka beli.
Karena bisa jadi, apa yang kita sebut “fashion ramah lingkungan” hari ini, adalah sisa konsumsi dunia pertama yang baru kita terima kemasannya saja. Isinya? Tetap limbah.