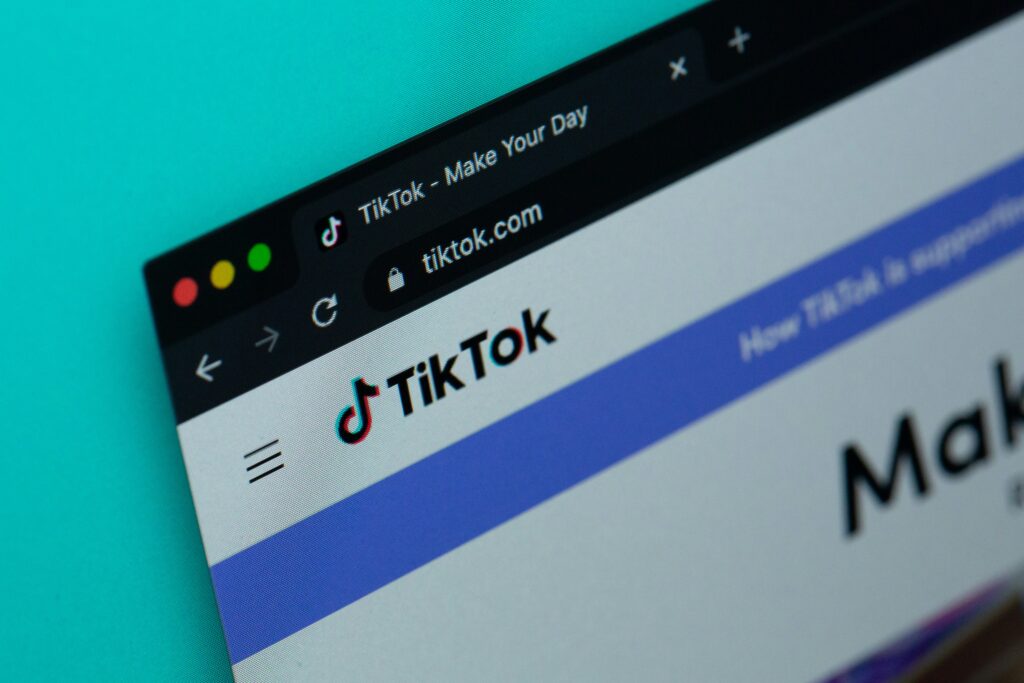Pernahkah kita menyadari betapa cepatnya waktu berlalu di usia produktif? Pagi datang, malam tiba, dan sebagian besar hari habis untuk bekerja. Kita sibuk mengejar target, memenuhi ekspektasi, dan terus bergerak dalam roda yang seolah tak pernah berhenti. Dalam banyak organisasi, setiap aktivitas diukur dari output-nya, setiap keputusan ditimbang dari dampaknya terhadap profitabilitas. Kita tumbuh dalam budaya yang menjadikan kerja bukan hanya sebagai sarana mencari nafkah, tetapi juga sebagai identitas sosial, bahkan sebagai penanda nilai moral.
Pandangan ini, tentu saja, tidak keliru. Dalam sistem ekonomi saat ini, mengejar efisiensi dan keuntungan merupakan sesuatu yang logis dan rasional. Namun, pernahkah kita bertanya: mengapa setiap bentuk pekerjaan harus selalu dinilai dari dampak ekonominya? Mengapa kebijakan, strategi, dan tindakan publik mesti terlebih dahulu dilihat dari sisi finansial semata?
Bagaimana jika kita membalik logika tersebut? Bahwa perusahaan tetap dapat mengejar keuntungan yang wajar, tetapi dengan menempatkan kesejahteraan dan waktu luang yang berkualitas bagi pekerjanya sebagai prioritas. Bahwa negara tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, namun dengan mempertimbangkan kualitas hidup, relasi sosial, dan ketahanan psikologis warga negaranya.
Di sinilah muncul dua gagasan yang saling terkait dan semakin banyak dibicarakan di berbagai belahan dunia: post-work dan post-capitalism. Post-work menyoroti perubahan peran kerja dalam kehidupan manusia, yaitu bagaimana kerja tidak lagi menjadi pusat kehidupan seperti saat ini. Sementara itu, post-capitalism menggambarkan transformasi sistem ekonomi yang mendasari perubahan tersebut, di mana nilai ekonomi tidak hanya ditentukan oleh modal dan produksi, tetapi juga oleh akses terbuka, teknologi digital, dan solidaritas sosial. Dengan memahami kedua konsep ini bersama, kita mendapat gambaran tentang bagaimana masa depan kerja dan ekonomi bisa menjadi lebih fleksibel, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan.
Pertanyaannya: apakah ide-ide semacam ini dapat relevan—bahkan mungkin—di Indonesia?
Post-Work dan Post-Capitalism: Menyoal Sentralitas Kerja
Post-work merujuk pada pemikiran bahwa kerja tidak harus menjadi pusat dari kehidupan manusia. Dalam masyarakat post-work, teknologi dan sistem sosial memungkinkan manusia hidup layak tanpa harus bekerja penuh waktu atau sepanjang hayat. Gagasan ini berangkat dari pemahaman bahwa kerja formal—sebagaimana kita kenal sekarang—bukanlah kodrat, melainkan konstruksi historis.

Sementara itu, post-capitalism adalah wacana yang membayangkan sistem ekonomi baru yang melampaui kapitalisme konvensional. Nilai ekonomi tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kepemilikan modal, tetapi juga oleh akses terbuka terhadap sumber daya, kerja kolaboratif, dan nilai-nilai solidaritas. Teknologi digital dan otomatisasi menjadi fondasi transformasi ini.
Di beberapa negara seperti Finlandia, Jerman, dan Kanada, telah dilakukan uji coba terbatas terhadap kebijakan seperti Universal Basic Income (UBI), pengurangan jam kerja, dan jaminan sosial universal. Eksperimen ini membuka kemungkinan baru bagi masyarakat untuk hidup dengan lebih bebas dari tekanan kerja rutin dan tuntutan pasar.
Indonesia: Realitas Sosial dan Peluang Struktural
Indonesia menghadapi tantangan yang khas. Sekitar 60 persen angkatan kerja berada di sektor informal (BPS, 2023). Di banyak wilayah, upah minimum belum mampu memenuhi kebutuhan dasar. Digitalisasi dan otomatisasi juga mulai mengancam stabilitas pekerjaan di sektor manufaktur dan jasa, terutama bagi tenaga kerja dengan keterampilan menengah ke bawah.
Program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan telah berkembang, namun cakupannya belum optimal. Banyak pekerja tidak tetap dan informal belum terproteksi. Di sisi lain, budaya kerja keras yang ditanamkan sejak dini, ditambah glorifikasi kesibukan, menjadikan masyarakat sulit membayangkan hidup tanpa kerja yang intensif.
Namun, bukan berarti wacana post-work tak relevan. Indonesia memiliki keunggulan demografis, semangat gotong royong, serta praktik ekonomi kolektif yang mengakar. Ekonomi digital yang tumbuh pesat, munculnya koperasi digital, dan komunitas berbasis solidaritas dapat menjadi jembatan menuju bentuk kerja yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Langkah Transisi: Dari Output ke Keutuhan Hidup
Jika Indonesia ingin mulai menjajaki arah post-work versi sendiri, sejumlah langkah strategis bisa dipertimbangkan:
Pertama, eksperimen kebijakan sosial. Pemerintah daerah dan BUMN dapat menjadi laboratorium kebijakan yang mendorong inovasi kesejahteraan. Misalnya, dengan menguji skema Universal Basic Income (UBI) berskala terbatas, ditujukan untuk kelompok rentan atau wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Atau, dengan menerapkan kebijakan empat hari kerja dalam sektor-sektor tertentu, terutama yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Eksperimen ini tidak hanya menguji dampak produktivitas secara kuantitatif, tetapi juga kualitas hidup secara menyeluruh: kesehatan mental, partisipasi keluarga, dan relasi sosial. Dampaknya bisa membuka jalan bagi pendekatan baru dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Kedua, transformasi tempat kerja. Dunia usaha perlu menggeser orientasinya dari sekadar mengejar output ekonomi menuju keseimbangan dengan aspek sosial dan psikologis. Ini berarti mendesain ulang struktur kerja agar lebih fleksibel, inklusif, dan berkeadilan. Bekerja dari rumah, jam kerja fleksibel, cuti untuk kepentingan keluarga, hingga pengakuan terhadap kerja nonformal seperti kerja domestik dan pengasuhan harus menjadi bagian dari ekosistem kerja yang baru. Jika diadopsi secara luas, pendekatan ini dapat menekan angka burnout, meningkatkan retensi tenaga kerja, serta memperkuat kohesi sosial di tempat kerja.
Ketiga, penguatan ekonomi komunitas. Model kerja berbasis solidaritas dan partisipasi—seperti koperasi digital, usaha komunitas, dan ekonomi berbagi—perlu diberi tempat lebih besar dalam perekonomian. Pemerintah dapat mendorongnya melalui insentif fiskal, kemudahan perizinan, perlindungan hukum, dan literasi digital. Selain menciptakan lapangan kerja alternatif, model ini juga mendistribusikan nilai ekonomi secara lebih merata dan membangun ketahanan lokal terhadap gejolak pasar global. Di era disrupsi digital, ini bisa menjadi fondasi penting bagi kedaulatan ekonomi rakyat.
Keempat, reformasi pendidikan. Kurikulum pendidikan nasional perlu dirancang ulang agar tidak sekadar mempersiapkan siswa untuk dunia kerja formal, melainkan untuk berkontribusi secara bermakna pada masyarakat. Ini berarti menanamkan nilai kolaborasi, empati, ekologi, dan kreativitas sejak dini. Dengan begitu, generasi mendatang tidak terperangkap dalam narasi sempit “kerja untuk bertahan hidup”, melainkan tumbuh sebagai warga aktif yang mampu menciptakan nilai sosial di berbagai ranah kehidupan. Jika berhasil, perubahan ini akan menciptakan lanskap baru pendidikan yang lebih responsif terhadap masa depan kerja yang semakin cair dan tidak terdefinisi secara kaku.
Pergeseran ini tentu tidak mudah. Ia membutuhkan perubahan dalam kebijakan, sistem insentif, serta narasi sosial. Peran media, pendidikan, dan elite politik akan menentukan seberapa jauh gagasan ini bisa dibawa ke ruang publik secara serius.
Penutup
Gagasan post-work bukanlah utopia. Ia adalah tawaran untuk membayangkan ulang hubungan manusia dengan waktu, produktivitas, dan makna hidup. Di tengah tekanan ekonomi, ketimpangan struktural, dan kelelahan kolektif yang makin terasa, inilah saatnya kita bertanya: hidup seperti apa yang layak kita bangun bersama?
Sebab pada akhirnya, nilai suatu bangsa tak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonominya, melainkan dari cara ia memperlakukan warganya—bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai manusia seutuhnya.